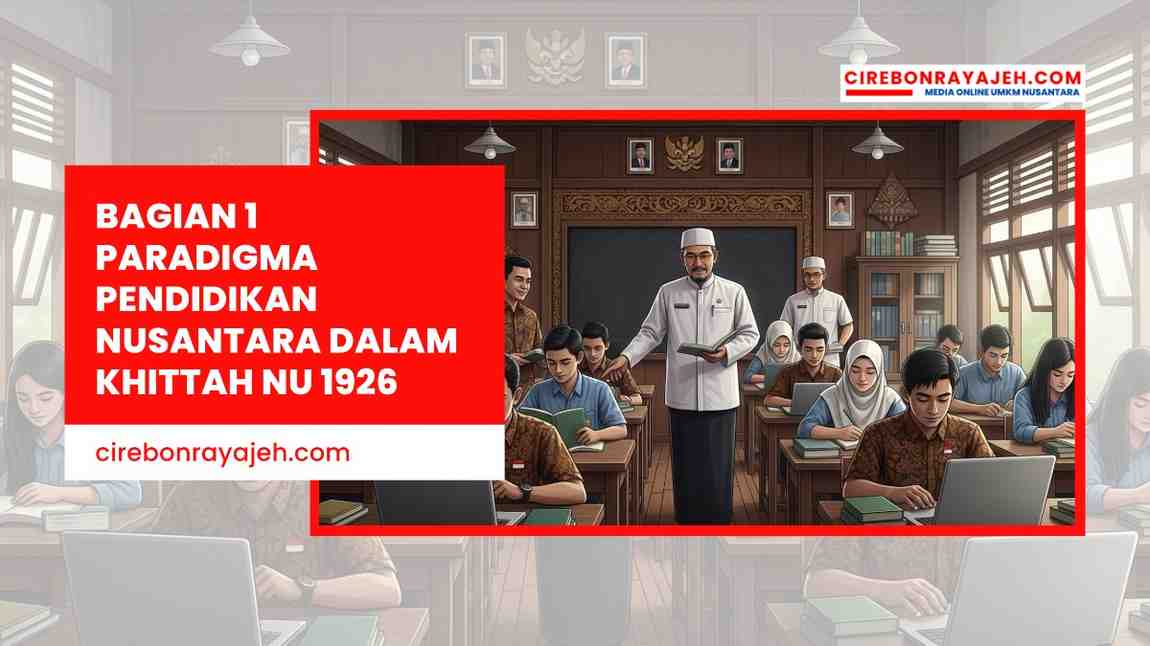[Cirebonrayajeh.com – Mondok Yu] “Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya.”
Frasa khittah NU 1926 tersebut menjadi pijakan filosofis penting untuk merumuskan paradigma pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan individu, tetapi juga pada aspek sosial, kolektif, nilai-nilai kemanusiaan dan kebahagiaan. Berikut ini saya uraikan secara mendalam: mulai dari pengenalan & masalah, analisis filosofis & sosiologis, lalu solusi nyata dan aplikatif untuk pendidikan di Nusantara, terutama dalam konteks pendidikan Islam dan lembaga-lembaga NU.
Pendahuluan: Menggali Akar Filosofi Pendidikan Nusantara
Pendidikan di Nusantara tidak berdiri di ruang hampa; ia terpaut kuat pada sejarah masyarakat, tradisi, dan keragaman budaya. NU (Nahdlatul Ulama), sejak kelahirannya tahun 1926 dalam khittah-nya, memberi penekanan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus hidup bermasyarakat, bahwa kebahagiaan manusia tidak mungkin tercapai secara sendirian, dan bahwa pendidikan harus mampu menjaga manusia dari bahaya—baik bahaya internal seperti kerusakan moral, maupun bahaya eksternal seperti ketidakadilan sosial atau tekanan budaya asing.
Namun lembaga pendidikan modern di Indonesia, termasuk lembaga Islam, seringkali terjebak dalam paradigma utilitarian: bagaimana siswa cepat “siap kerja”, bagaimana prestasi standar ujian nasional tinggi, bagaimana kompetisi global bisa dimenangkan. Sementara aspek kebersamaan, spiritualitas, nilai lokal, serta makna kebahagiaan manusia sering kurang mendapat ruang. Artikel ini berupaya menarik kembali paradigma pendidikan Nusantara yang tersirat dalam khittah NU 1926, dengan menggunakan kerangka filsafat pendidikan Islam, sosiologi pendidikan, antropologi, dan manajemen mutu kurikulum.
Identifikasi Masalah dalam Pendidikan Nusantara
Sebelum kita merumuskan apa yang harus dilakukan, penting untuk memahami tantangan riil yang sedang dihadapi pendidikan di Nusantara. Masalah-masalah ini berakar pada perubahan sosial, tuntutan global, perubahan budaya, dan kelemahan sistem. Dengan memahami akar masalah, kita bisa merumuskan solusi yang bukan hanya retorik, tapi bisa diimplementasikan dalam konteks lembaga pendidikan NU, sekolah umum, pesantren, dan komunitas.
Krisis Individualisme dan Melemahnya Nilai Kolektivitas
Salah satu gejala yang mencolok dalam sistem pendidikan modern adalah betapa besar tekanan pada individu: prestasi pribadi, ranking, skor, kompetisi. Siswa dituntut untuk unggul secara individu—sering dalam penilaian standar—tanpa cukup diberi ruang untuk belajar hidup bersama, saling menolong, bergotong-royong, berbagi, serta keberpihakan pada kepentingan bersama.
Secara sosiologis, Durkheim misalnya mengatakan bahwa masyarakat modern perlu solidaritas organik, tetapi kalau sekolah hanya membentuk individu yang kompetitif, jaringan solidaritas sosial melemah. Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian menunjukan bahwa nilai gotong royong dan partisipasi komunitas dalam pendidikan mulai menurun, terutama di daerah perkotaan dan di sekolah swasta yang lebih “elit”.
Pendidikan yang Terjebak dalam Orientasi Ekonomi Semata
Pendidikan seringkali dipahami sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan, menaikkan status sosial, atau mengikuti persaingan global. Fokus ini bukan tanpa manfaat, tetapi jika menjadi satu-satunya orientasi, maka aspek moral, spiritual, dan kebahagiaan batin menjadi terabaikan.
Ada laporan bahwa siswa stres tinggi karena tekanan prestasi, persaingan sekolah/materi, orientasi uang, dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan karakter. Riset tentang dampak standar ujian nasional di Indonesia menunjukkan bahwa guru dan siswa cenderung mengajar dan belajar hanya untuk “lulus” – bukan untuk membangun pemahaman, empati, kepekaan sosial. Ini menyebabkan pembelajaran menjadi mekanistik dan kurang bermakna.
Hilangnya Kearifan Lokal dalam Kurikulum
Dalam upaya menstandarkan pendidikan nasional, ada risiko bahwa kearifan lokal—nilai-nilai budaya, bahasa daerah, etika lokal—terpinggirkan. Kurikulum pusat kadang terlalu generik, kurang sensitif terhadap konteks lokal. Padahal Nusantara sangat kaya: setiap daerah punya tradisi, bahasa, adat, dan cara pandang yang khas.
Beberapa studi memperlihatkan gap antara kurikulum dan budaya lokal. Misalnya, penelitian “Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan” menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar kearifan lokal, masih banyak sekolah belum mengoptimalkan pemanfaatannya dalam metode dan materi pembelajaran.
Juga, artikel “Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal: Menjaga Tradisi dan Membangun Masa Depan Masyarakat Banjarmasin” menunjukkan bahwa integrasi tradisi budaya Banjar dalam pendidikan membantu menjaga identitas budaya generasi muda.
Paradigma Pendidikan Nusantara Menurut Khittah NU 1926
Setelah mengidentifikasi masalah, di bagian ini kita mengupas secara filosofis, teologis, sosiologis, antropologis apa yang sesungguhnya terkandung dalam khittah NU, dan bagaimana ini bisa menjadi fondasi paradigma pendidikan yang lebih utuh dan bermakna. Juga dikaitkan dengan teori-teori pendidikan Islam dan antropologi pendidikan agar paradigma menjadi terstruktur.
Pendidikan sebagai Proses Sosial dan Kolektif
Khittah 1926 menekankan bahwa manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia hidup bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, ini berarti belajar bukan hanya tentang konten akademik, tapi tentang bagaimana peserta didik belajar hidup bersama—di dalam komunitas, dalam kelompok, dalam lembaga dengan interaksi sosial yang positif.
Dari filsafat pendidikan Islam, konsep ummah, masyarakat, khalifah, amanah, semua mendorong bahwa individu bertanggungjawab terhadap orang lain dan lingkungan sosial. Tokoh seperti Al-Ghazzali & Ibnu Khaldun memberikan perhatian bahwa kesejahteraan individu terikat dengan kesejahteraan sosial.
Dalam pendidikan sosiologis dan antropologis, sekolah sebagai lembaga sosial memiliki fungsi integratif: membentuk solidaritas, mempromosikan interaksi antar budaya, menjaga jaringan sosial. Untuk NU, hal ini sudah tercermin dalam sistem pesantren: santri hidup bersama, dengan tradisi musyawarah, gotong royong, permusyawaratan, dan kebersamaan.
Pendidikan untuk Kebahagiaan dan Perlindungan
Khittah selanjutnya menyatakan manusia “berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya.” Ini mengandung dua hal: pertama, bahwa pendidikan harus akhirnya menolong peserta didik mencapai keadaan sejahtera—secara lahir dan batin; kedua, bahwa pendidikan harus melindungi dari bahaya—bahaya moral, bahaya sosial, bahaya psikologis, bahaya kekerasan budaya, dan bahaya ketidakadilan.
Dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya tentang ilmu (ʿilm), tapi juga hikmah dan adab. Pendidikan yang ideal memperhatikan keseimbangan ilmu, iman dan akhlak. Pendidikan yang aman bagi isi jiwa peserta didik sangat penting: penghormatan pada hak asasi manusia, pada martabat, pada keberagaman. Sekolah, pesantren, madrasah sebagai ruang yang membentuk rasa aman (fisik dan psikologis), sekaligus budaya pelindung terhadap nilai-nilai luhur.
Data empiris: Studi “Transformasi Kearifan Lokal Jawa dalam Pendidikan Karakter Sekolah Dasar” mencatat nilai-nilai seperti toleransi, rendah hati, peduli sosial, cinta damai, dan kepedulian terhadap lingkungan (memayu hayuning bawana) sebagai transformasi nilai lokal yang membantu peserta didik tidak hanya belajar akademik tetapi juga merasa aman, dihargai, memiliki makna.
Rumah Jurnal UIN Alauddin
Integrasi Nilai Islam, Humanisme, dan Kebudayaan Nusantara
Paradigma Nusantara tidak berarti “lokal saja” tanpa universalitas, dan bukan Islam eksklusif tanpa menghargai budaya lokal. Seperti filosofi NU: Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inklusif, yang memadukan iman, adab, karya, kebangsaan, dan kemanusiaan. Paradigma pendidikan Nusantara idealnya menggabungkan:
- Nilai-nilai Islam: akhlak, toleransi, keadilan, kasih sayang, amanah, ikhlas, tolong-menolong, pengampunan, dsb.
- Nilai manusia universal / humanisme: penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan berpikir, hak asasi, kerja sama antar etnis/agama, perdamaian.
- Nilai budaya Nusantara: kearifan lokal, gotong royong, musyawarah, toleransi antar suku/bahasa, penghormatan terhadap leluhur, pelestarian alam, simbol budaya lokal.
Dari antropologi pendidikan, identitas budaya sangat penting agar peserta didik merasa akarnya nyambung, tidak alienasi, tidak kehilangan makna. Ini juga mendukung motivasi belajar, sebab belajar menjadi bagian dari hidup, bukan sekadar tugas.
Solusi dan Implementasi Paradigma Pendidikan Nusantara
Paradigma tanpa tindakan nyata akan tetap menjadi wacana. Di bagian ini kita uraikan solusi-solusi konkret, kerangka pengelolaan, model kurikulum, metode pedagogi, serta langkah-langkah praktis agar paradigma khittah NU 1926 dapat dihidupkan kembali di sistem pendidikan Nusantara.
Reorientasi Kurikulum Pendidikan
Memasukkan muatan kearifan lokal sebagai inti, bukan tambahan
Kurikulum nasional dan daerah perlu memiliki ruang formal untuk nilai-nilai lokal: misal budaya, tradisi, bahasa lokal, cara pandang lokal. Ini bukan hanya muatan muatan muatan lokal sebagai “pelengkap” ekstrakurikuler, melainkan sebagai bagian dari kompetensi sikap dan karakter yang diukur.
Contoh: di Sulawesi Selatan, penelitian “Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia” mengungkap bahwa materi pelajaran yang menyertakan cerita lokal, bahasa daerah, dan ungkapan budaya lokal meningkatkan motivasi siswa dan memperkuat identitas budaya mereka.
Ejournals Umma
Keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak dalam muatan kurikulum
Kurikulum harus mendesain kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Di lembaga NU (pesantren, madrasah), hal ini dapat dikembangkan lewat mata pelajaran agama, pendidikan karakter, literasi moral, lingkungan hidup, dan mata pelajaran umum yang dikaitkan dengan etika Islam dan nilai kebangsaan.
Penerapan kurikulum yang fleksibel dan kontekstual
Setiap daerah punya kondisi: budaya, sumber daya, tantangan lokal berbeda. Oleh karena itu, kurikulum harus memungkinkan adaptasi lokal, pengembangan silabus/materi lokal oleh guru/komunitas, sehingga relevan dengan kehidupan peserta didik.
Penerapan Pedagogi Berbasis Komunitas
Model pembelajaran kolaboratif dan interaktif
Guru bukan lagi sumber tunggal ilmu, tetapi fasilitator yang memicu dialog, diskusi kelompok, musyawarah, proyek komunitas. Peserta didik aktif membangun pengetahuan, belajar gotong royong, bekerja dalam tim, saling membantu.
Penguatan lembaga pendidikan berbasis NU & masyarakat lokal
Pesantren, madrasah, TPQ, lembaga keagamaan NU lainnya bisa menjadi pusat pendidikan karakter dan kebajikan sosial. Kegiatan seperti pengabdian masyarakat, kerja bakti, kegiatan sosial keagamaan, ekstrakurikuler budaya lokal, harus menjadi bagian rutin.
Pembelajaran berbasis masalah nyata di lingkungan lokal
Metode pembelajaran masalah (problem-based learning), proyek nyata (project-based learning) yang mengajak siswa/murid meneliti kondisi lokal mereka; memecahkan masalah sosial, lingkungan, budaya dalam komunitas mereka.
Penguatan Karakter dan Literasi Sosial
Program pendidikan karakter yang sistematis
Tidak sekadar slogan, tetapi dirancang dengan indikator-indikator karakter: jujur, amanah, tanggung jawab, empati, toleransi. Lembaga NU sudah memiliki tradisi educative moral yang kuat (kitab, sorogan, munajat, tahlilan, zikir, silaturahim) — ini harus diintegrasi dalam struktur sekolah, madrasah, dan kegiatan sehari-hari.
Literasi budaya dan literasi sosial
Literasi budaya: membaca/mempelajari budaya lokal, bahasa daerah, sejarah lokal, sastra lokal, seni tradisional. Literasi sosial: pemahaman tentang keadilan sosial, kesenjangan, hak asasi, kepekaan terhadap marginalisasi, inklusi.
Studi “Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural” menunjukkan bahwa pendidikan multikultural yang memasukkan nilai lokal membantu memperkuat identitas nasional sekaligus mengembangkan toleransi antar suku/bahasa/agama.
Pelatihan dan pengembangan profesional guru
Guru perlu dibekali kompetensi memanfaatkan kearifan lokal, pedagogi humanistik, metode dialogis dan kolaboratif, serta kemampuan manajemen kelas yang memupuk kebersamaan, bukan kompetisi semata. Pelatihan berkelanjutan, komunitas praktisi (teacher community of practice) diperlukan.
Penutup: Membangun Masa Depan Pendidikan Nusantara
Paradigma Pendidikan Nusantara yang tersirat dalam khittah NU 1926 bukanlah nostalgia kosong; ia adalah fondasi filosofis dan moral yang sangat relevan jika kita ingin membangun pendidikan yang tidak sekadar mencetak manusia produktif, tetapi manusia utuh: yang berakhlak, peduli pada sesama, terhubung dengan budaya, berpegang pada nilai-nilai Islam, dan mampu menciptakan kebahagiaan bagi dirinya dan masyarakat.
Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia—khususnya lembaga NU—memiliki tanggung jawab besar: menjadi motor transformasi paradigma ini. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mendukung melalui kebijakan kurikulum, sumber daya, pelatihan guru, dan pengakuan kearifan lokal. Komunitas lokal dan keluarga juga punya peran sentral: mentransmisikan nilai budaya, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab sosial.
Saatnya kita bergerak dari pendidikan yang membuat individu “kompetitif saja” menjadi pendidikan yang membuat manusia “holistik”: yang mengembangkan iman, akal, hati, karakter, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menolak bahaya terhadap martabat manusia. Dengan paradigma Nusantara berbasis khittah NU, pendidikan akan menjadi kekuatan pemersatu dan penggerak kesejahteraan sejati.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud dengan Paradigma Pendidikan Nusantara menurut khittah NU 1926?
Paradigma ini menekankan bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai kebersamaan, kebahagiaan, serta perlindungan terhadap martabat manusia, dengan integrasi Islam, humanisme, dan budaya lokal Nusantara.
2. Mengapa pendidikan modern di Indonesia cenderung terjebak pada orientasi ekonomi?
Karena sistem evaluasi dan kurikulum sering menekankan kompetisi, standar ujian, serta “siap kerja”, sehingga aspek karakter, nilai sosial, dan kearifan lokal kurang diperhatikan.
3. Bagaimana cara menerapkan paradigma pendidikan berbasis khittah NU dalam kurikulum sekolah?
Dengan memasukkan nilai kearifan lokal dalam materi inti, mengembangkan metode kolaboratif berbasis komunitas, dan memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islam dan budaya Nusantara.
4. Apa peran pesantren dan lembaga pendidikan NU dalam paradigma ini?
Pesantren dan madrasah NU berperan sebagai pusat pendidikan karakter, kebajikan sosial, dan integrasi nilai agama, budaya, serta literasi sosial yang menumbuhkan solidaritas masyarakat.
5. Bagaimana paradigma ini menjawab tantangan globalisasi?
Paradigma pendidikan Nusantara tidak menolak modernitas, tetapi menyaring nilai universal yang relevan sambil tetap menanamkan akar budaya, identitas lokal, dan spiritualitas untuk menghadapi tantangan global.